Ketika Presiden RI, Soeharto, turun pada 21 Mei 1998, kota Jakarta layaknya sebuah area perang. Lebih dari 2500 orang meninggal akibat bentrok dengan aparat dan kebakaran yang terjadi dimana-mana meluluhlantakkan Jakarta. Dalam kerusuhan tersebut berhembus isu nasionalisasi, di mana sentimen terhadap salah satu etnis di Indonesia dimunculkan ke permukaan. Isu tersebut membuat warga asing yang tinggal di Jakarta pindah atau untuk sementara terbang ke negara lain menunggu kerusuhan berakhir. Di antara orang asing yang pergi ke luar negeri dalam kerusuhan itu, terdapat 30 eksekutif dan anggota keluarga dari dua perusahaan multinasional, yakni Thames Water dan Suez Lyonnaise des Eaux. Empat bulan sebelumnya, perusahaan tersebut telah mengambil alih pengaturan air di Jakarta, berpartner dengan anak-anak Soeharto dan “kroni-kroninya.” Meski kepergian direktur perusahaan multinasional tersebut hanya sementara untuk menunggu berakhirnya kerusuhan, namun teknisi lokal yang berada di kantor kerja tidak tahu, bagaimana mereka harus mengendalikan sistem air yang telah dijalankan. Selain itu, kerusuhan menghambat pasokan zat-zat pemurni air seperti Chlorine atau Alumunium Sulphate. Keadaan tersebut memicu kelangkaan air di Jakarta dan penduduk terancam kekurangan air bersih. Kendalanya, petinggi Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut direktur PAM Jaya sejak PAM Jaya diambil alih oleh dua perusahaan multinasional tersebut, kekuasaan atau otoritas legal dipegang oleh perusahaan multinasional tersebut.
Privatisasi air di Indonesia adalah sebuah cermin dari bagaimana kepentingan dari korporasi air global, penguasa yang korup serta diktator dan pinjaman Bank Dunia menekan untuk dilakukannya privatisasi. Sampai saat ini, sebagian besar rakyat miskin di Jakarta masih hidup tanpa jasa air yang layak. Privatisasi air di Indonesia ini awalnya terjadi pada awal 1990 ketika Bank Dunia menyetujui untuk menyediakan pinjaman US $ 92 juta untuk infrastruktur air. Privatisasi tersebut juga berlangsung dengan saran dari Bank Dunia. Secara umum, privatisasi di Indonesia dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah privatisasi sebelum krisis ekonomi 1997, dan privatisasi tahap kedua setelah krisis ekonomi dan masuknya IMF ke Indonesia.
Privatisasi tahap pertama berlangsung dengan pinjaman multilateral dari bank Dunia dan pinjaman bilateral dari Jepang, perusahaan multinasional asal Inggris dan Perancis, yakni Suez dan Thames, yang memulai untuk mengambil alih sistem air publik. Yang menarik, privatisasi ini melibatkan konglomerasi Indonesia atas nama PT Kekar Pola Airindo. Di belakang Kekar Pola Airindo, terdapat nama Salim Group, yakni Anthony Salim, dan Sigit Harjojudanto. Dua orang ini bisa dibilang sebagai “kroni” dari pemerintahan Soeharto, terutama melihat hubungan keluarga antara Soeharto dan Sigit, serta hubungan bisnis antara Soeharto dan Salim Group.
Kehadiran Thames Water Overseas di Indonesia pertama kali pada tahun 1993. Perusahaan multinasional asal London ini menggandeng putra Soeharto, Sigit Harjojudanto, sebagai partnernya. Padahal, Sigit bukanlah seorang pemain yang mengerti benar pengelolaan air. Thames membentuk perusahaan lokal dan kemudian memberi Sigit 20 % dari keuntungan. Mengutip pernyataan Teten Masduki, “Setiap perusahaan multinasional di Indonesia selalu bekerjasama dengan kroni Soeharto. Dari semua sektor, listrik, minyak, air, dan lainnya, merupakan bentuk oligarki korupsi. Perusahaan itu ingin mendapatkan perlindungan politik. Anak-anak Soeharto tersebut mendapatkan bagian tanpa menaruh investasi, hanya untuk pengaruh secara politik.” Kemudian, terjadi konsesi atas pembagian kerjasama, Sigit bekerjasama dengan Thames membentuk Kekar Pola Airindo, sedang Salim Group dengan Suez membentuk PT Garuda Dipta Nusantara. Hal ini dilakukan karena hukum nasional saat itu melarang adanya investasi asing di bidang penyediaan air.
Ketika terjadi kerusuhan seperti tergambar pada ilustrasi di atas, petinggi Thames dan Suez mulai memikirkan kembali masa depan bisnis mereka di Indonesia. Karena telah terikat kontrak di awal selama 25 tahun, dua perusahaan multinasional itu memutuskan untuk terus beroperasi di Indonesia, namun kali ini privatisasi dilangsungkan langsung menggandeng PAM Jaya, karena menurunnya peran dari “kroni-kroni” Soeharto. Dengan negosiasi yang berlangsung dengan PAM, akhirnya Thames dan Suez merestrukturisasi manajemen mereka termasuk kerjasama dengan Kekar Pola dan Garuda Dipta. Pada tahun 2001, dibentuklah PT PAM Thames Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya, dengan menggandeng PT Terra Meta Phora dan PT Bangun Cipta Sarana.
Tujuan awal privatisasi air adalah untuk menyediakan air bersih di Indonesia secara lebih luas. Indonesia, menurut catatan UNDP, memiliki 55 % penduduk yang rawan akan akses air bersih. Banyak penyebab mengapa persediaan air bersih di Indonesia menurun, pertama karena kerusakan sungai, kedua karena pencemaran air tanah, dan ketiga karena pencemaran sungai. Di Jakarta, air bersih menjadi sebuah permasalahan karena banyak air yang telah tercemar polutan atau bakteri tanah. Padahal, air adalah sumber daya alam yang sangat penting nilainya bagi manusia.
Privatisasi, sebagaimana dituliskan Stephen Green di sub bab terdahulu, mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan, meminimalisir pelaksanaan korupsi dalam tata kelola perusahaan, mengembalikan aset-aset negara yang disalahgunakan oleh oknum pejabat negara ketika mengelola aset tersebut, dan yang paling penting adalah memperbaiki layanan publik. Pada kenyataannya, setelah dilakukan privatisasi air oleh PAM Thames Jaya dan PAM Lyonnaise Jaya, pelayanan air tidak meningkat secara signifikan, hanya daerah-daerah di pusat kota seperti Menteng dan Pondok Indah yang meningkat pelayanannya secara signifikan. Kenyataannya, tarif air di Jakarta justru mengalami kenaikan. Lebih lanjut, PAM Jaya masih meminta diberikannya subsidi dari pemerintah terkait dengan perbaikan infrastruktur. Hal ini tentunya sangat aneh dan absurd secara teoritis, di mana privatisasi seharusnya dapat menekan harga lebih murah dan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara ke swasta, namun pada kenyataannya dalam privatisasi air di Jakarta, pemerintah masih melakukan subsidi dan tarif air naik. Menurut laporan WALHI, dari sisi pelayanan, pasca privatisasi tahap kedua kepada kedua mitra asing, tidak mengalami perbaikan dan peningkatan yang berarti. Ini terlihat dari sejumlah indikator utama kualitas pelayanan air minum. Target pertambahan pelanggan dari tahun 1998-2000 tidak mencapai ketentuan kontrak, dan lebih rendah dibanding pertumbuhan sebelumnya oleh PAM Jaya. Target teknis pemakaian air tidak tercapai, tetap dibawah kinerja PAM Jaya yang telah diprivatisasi.
Tingkat kebocoran pipa juga tidak sesuai dengan klausul dalam kontrak dan harapan masyarakat. Tingkat kebocoran pada saat dikelola PAM Jaya sebesar 53%, kini berkisar pada angka 48%. Namun, untuk menekan tingkat kebocoran (non revenue water), kedua mitra asing hanya melakukan pembatasan pengoperasian mesin pompa yang terdapat di setiap instalasi. Dampaknya, sejumlah daerah dalam jangkauan pelayanannya malah mengalami kekurangan air.
Sementara dari sisi kualitas air relatif tidak berubah sebelum dan sesudah privatisasi. Bahkan untuk beberapa indikator seperti konsentrasi deterjen, setelah privatisasi, kualitas airnya justru menurun. Pada 1998 misalnya, konsentrasi deterjen mencapai 0,12 mg/l. Demikian juga pada 1999 dengan konsentrasi deterjen sebesar 0,17 mg/l. Padahal standar konsentrasi deterjen adalah 0,05 mg/l. Bandingkan dengan sebelum privatisasi, konsentrasi deterjen masih memenuhi standar seperti pada 1993 (0,031 mg/l) dan 1994 (0,016 mg/l).
Tarif air di Jakarta rata-rata Rp. 5.000 permeter kubik, termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Tarif tinggi karena sejak awal kontrak sudah mahal, yakni Rp. 1.700. Tarif terus mengalami kenaikan karena inflasi, dan kenaikan tarif otomatis terjadi tiap semester (6 bulan). Dari tarif demikian, sebanyak Rp. 4.600 digunakan untuk membayar imbalan kepada operator asing (PAM Suez Lyonnaise dan PAM Thames Jaya). Sisanya untuk bayar utang PDAM kepada pemerintah, defisit, serta badan regulator. Apabila kenaikan tarif air otomatis tidak disetujui pemerintah, maka kedua operator asing akan membebankan selisih Water Charge (imbalan air) dan Tarif Air kepada Pemerintah DKI sebagai utang. Saat ini Pemerintah DKI justru memiliki hutang sekitar Rp. 900 milliar kepada operator asing karena tarif air tidak dinaikkan dalam periode 1998-2001. Sementara mengenai tingkat layanan, menurut pengakuan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelanggan dan Masyarakat (FKPM), kualitas air minum setelah privatisasi tetap keruh dan berbau tidak sedap. Selain mengeluh soal kualitas air minum, warga juga mempersoalkan distribusi air bersih yang tidak merata. "Rumah yang berada di pinggir jalan besar bisa mendapat air dengan lancar, sementara rumah di tengah perkampungan airnya sering mati," kata Ahmad Syarifudin, Ketua Dewan Kelurahan (Dekel) Semper Barat, Jakarta Utara. Distribusi air yang tidak merata akibat kecilnya tekanan air dikeluhkan anggota Lembaga Masyarakat Kota Jakarta Barat, Sukarlan.
Relasi Kuasa Dalam Privatisasi Air
Discourse privatisasi air di Indonesia, sebagaimana penulis ungkapkan di atas, sangat absurd secara teoritis. Terdapat “gap” antara teori privatisasi yang mengatakan bahwa privatisasi meningkatkan efisiensi perusahaan dan meningkatkan profesionalitas perusahaan, dan pelaksanaan di lapangan, bahwa privatisasi air tidak meningkatkan kualitas air berikut pelayanannya. Penjelasan yang ditulis sebelumnya, terlihat bahwa pengetahuan akan privatisasi merupakan bentuk legitimasi Barat dengan kekuatan modalnya untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Bentuk arsitektur keuangan global berikut doktrin liberalismenya merupakan awal dari legitimasi Barat. Berakhirnya Perang Dingin, disebutkan oleh Abrahamsen, merupakan sebuah konteks internasional baru yang mendorong hegemoni Barat. Hancurnya kekuatan komunisme sebagai rival ideologi liberalisme telah menggeser sistem internasional menjadi unipolar.
SAP dan berbagai kebijakan IMF sebagai bagian dari arsitektur keuangan global telah mendorong dilakukannya privatisasi. Dalam kasus privatisasi air di Indonesia, Letter of Intent Indonesia-IMF 1998-2003 merupakan instruksi signifikan untuk mengeliminir kontrol negara dalam pembangunan. Salah satu pengejawantahan dari eliminasi kontrol negara adalah privatisasi, khususnya sektor air. Dengan kepemilikan modal yang tidak seimbang, privatisasi di era globalisasi tidak hanya merupakan “swastanisasi”, namun menjadi “asing-isasi”. Selain dalam kasus privatisasi air ini, privatisasi Indosat juga menjadi bukti nyata adanya “asing-isasi” ketika Singapore Telecommunicatons mendominasi kepemilikan saham di Indosat, atau privatisasi Semen Gresik yang terdapat kekuatan perusahaan multinasional Cemex di belakangnya.
Fukuyama (1993) dengan meyakinkan dalam bukunya The End of History and The Last Man mengajukan kesimpulan mengenai berakhirnya sejarah yang diikuti dengan kemenangan demokrasi-kapitalisme sebagai bentuk akhir pemerintahan di dunia ini. Tesis yang hampir sama juga diajukan Kenichi Ohmae (1997) dalam The End of Nation State yang mengatakan bahwa globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Tulis Ohmae, globalisasi bukanlah sebuah pilihan bagi negara-negara di dunia, melainkan sebuah keniscayaan. Pemikiran neoliberalisme yang menjadi buzzword bagi globalisasi ekonomi telah dilegitimasi dalam rangkuman pemikiran, salah satunya melalui Washington Consensus. Kemudian, butir-butir dalam Washington Consensus itu muncul secara konkrit dalam Letter of Intent IMF atau kebijakan-kebijakan Bank Dunia.
Di dalam negeri, rezim yang cenderung otoriter melalui berbagai kekuasannya, turut berperan dalam memuluskan langkah privatisasi ini dengan turut menikmati keuntungan dari adanya privatisasi ini. Dalam kasus ini, di awal masuknya Suez dan Thames, Sigit dan Salim Group turut mendapat keuntungan atas masuknya dua perusahaan multinasional tersebut.
Relasi kuasa dan pengetahuan kemudian menjadi sangat nyata. Hubungan antara discourse, power, dan knowledge yang dikemukakan Foucalt terlihat dalam kasus privatisasi air ini. Discourse untuk adanya privatisasi air di Indonesia telah didorong oleh knowledge yang berkembang selama ini melalui Washington Consensus dan pengalaman privatisasi negara lain. Dalam discourse tersebut, terdapat kuasa kepentingan modal yang dicerminkan dari perusahaan multinasional (yang umumnya berasal dari Barat). Kelangsungan privatisasi juga didorong oleh rezim di dalam negeri karena kepentingan-kepentingan ekonomi di dalamnya, sehingga hubungan antara discourse dan power juga terlihat. Adanya kekuasaan yang mendapatkan keuntungan telah membuat discourse untuk dilangsungkannya privatisasi membuat proyek ini terus berlanjut.
Hubungan antara discourse, power, dan knowledge dalam kasus ini membuat sebuah bentuk hubungan bisnis semata dengan sistem “patron-klien”. Padahal, dalam kasus ini, air merupakan komoditas strategis publik yang seharusnya tidak dikelola dengan logika bisnis. Naiknya harga air dalam privatisasi di Indonesia membuat posisi kaum miskin menjadi termarjinalkan. Mereka tidak bisa mengakses air bersih akibat mahalnya harga air. Dengan kondisi yang seperti ini terus menerus, posisi rakyat miskin menjadi makin kritis. Penduduk miskin Jakarta sepertinya mustahil untuk membayar air sebesar Rp.5000,- per kubik jika pendapatan mereka di bawah Rp.10.000,- atau Rp.20.000,- per harinya (standar dari Bank Dunia mengenai kategori extreme poverty dan poverty).
Kualitas air buruk, terjadinya kebocoran air, serta naiknya harga air yang masih disubsidi pemerintah membuat privatisasi air perlu ditinjau kembali. Dengan ini, pertanyaan “Untuk siapa wacana itu bekerja?” menjadi sangat tepat untuk direnungkan. Namun demikian, tidak semua bentuk privatisasi gagal dari berbagai indikator. Privatisasi air di Brazil, misalnya, dapat dikatakan berhasil dalam fungsi penyediaan air serta masalah harga air. Privatisasi tersebut berhasil dengan pengawasan lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization yang memantau proses privatisasi air oleh perusahaan multinasional. Privatisasi Indosat yang menuai banyak kontroversi, sebaliknya sangat berhasil dalam menurunkan harga atau tarif kepada publik. Dampak yang dirasakan konsumen telepon seluler adalah turunnya tarif komunikasi dan membuat pasar telepon seluler menjadi lebih kompetitif.
Dengan segala konteks global; globalisasi yang membuat terhapusnya batas-batas negara termasuk batas perputaran uang, dan pemikiran neoliberal yang mengarus utama, privatisasi air di Indonesia yang melibatkan perusahaan multinasional dimungkinkan terjadi. Wacana privatisasi bukanlah sebuah wacana yang bebas nilai, dengan melihat bagaimana pengetahuan-pengetahuan dalam studi pembangunan dibentuk oleh lembaga keuangan global. Dengan melihat kekuatan yang ada di belakang privatisasi air di Indonesia ini dan menonjolnya aspek kuasa ini, dapat kita pahami mengapa pada akhirnya privatisasi gagal dalam menjawab permasalahan penyediaan air bersih di Indonesia, terutama akses air untuk penduduk miskin.
Penutup
Dunia mencoba menawarkan solusi atas permasalahan program-program IMF yang cenderung “one size fits for all”. Salah satu karya yang menarik perhatian publik adalah buku Joseph Stiglitz “Globalization and Its Discontents” yang menawarkan solusi yang disebut Post-Washington Consensus. Stiglitz mencoba merumuskan perlunya modal sosial guna mengentaskan masalah kemiskinan dan mencoba menekankan pada aktivitas non-ekonomi yang tidak hanya menekankan pada permasalahan perekonomian. Namun, pemikiran Post-Washington Consensus ini juga bukan solusi sempurna. Banyak kritik dialamatkan terhadap penganut Post-Washington Consensus seperti Stiglitz, Jeffey Sachs, atau Kanishka Jayasuriya. Dari sini, banyak analisis yang berkembang, dan muncul dialektika-dialektika tersendiri dalam ranah studi pembangunan, ekonomi, maupun hubungan internasional.
Namun dalam rangka memahami wajah peradaban Barat melalui pemikiran-pemikiran kontemporer – terutama pemikiran yang berakar dari tulisan Adam Smith, sebuah kritik muncul berkenaan dengan relasi antara kuasa dan pengetahuan. Pemikiran yang selama ini banyak ditularkan oleh pemikir-pemikir Barat kemudian dapat membentuk sebuah hegemoni, terutama melalui segitiga : ide, kapabilitas material, serta institusi. Merujuk pada pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni, sebuah hegemoni dapat dilawan dengan adanya organic intellectual. Artinya, posisi kaum intelektual sangat strategis dalam mengkonstruksi pemikiran serta menularkan pemikiran-pemikirannya dalam level yang lebih luas. Hegemoni Barat yang telah dibentuk melalui ide-ide neoliberalnya, institusi keuangan global, serta kekuatan ekonomi yang besar, salah satunya melalui perusahaan multinasional bukan tidak mungkin suatu saat akan bergeser. Kemudian ketika hegemoni itu bergeser, relasi kuasa dan pengetahuan pun akan bergeser kepada “penguasa” baru dunia; untuk kembali melanggengkan dan mereproduksi kekuasaannya.
Referensi
Abrahamsen, Rita. Disciplining Democracy: Good Government and Development Discourse in Africa. (New York: Zed Books, 1999).
Dickson, Anna K. Development and International Relations: A Critical Introduction, (Cambridge: Polity Press, 1997).
Green, Stephen. “Privatization in The Former Soviet Bloc: Any Lesson for China?”, The Royal Institute of International Affairs Asia Program Working Paper, No. 10, November 2003.
Green, Stephen. “Privatization in The Former Soviet Bloc: Any Lesson for China?”, The Royal Institute of International Affairs Asia Program Working Paper, No. 10, November 2003.
Hayami, Yujiro. “From Washington Consensus to Post Washington Consensus: Retrispect and Prospect”, dalam Asian Development Review, Vol. 20, No. 2, Tahun 2003.
Santosa, Setyanto P. “Quo Vadis Privatisasi BUMN?” dalam http://www.pacific.net.id/pakar/setyanto/tulisan_02.html, diakses pada tanggal 15 Juni 2008 pukul 10.50 WIB.
Setiawan, Bonnie. Menggugat Globalisasi, (Jakarta: INFID, 2000).
Setiawan, Bonnie. “The IMF Burden: The IMF has enriched corrupt official while burdening ordinary Indonesian with debts,” dalam http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/11.html, diakses pada tanggal 20 November 2008 pukul 20.56 WIB.
Sojavo, Herman. “Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil,” dalam http://www.citizen.org/documents/privatizationfiascos.pdf, diakses pada tanggal 11 November 2008 pukul 21.17 WIB.
Wahyudi, Indra. “Privatisasi Air Kabinet Yudhoyono,” dalam http://wong-mbatu.com/utama/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=9 diakses pada tanggal 11 November 2008 pukul 21.35 WIB.
Wahyudi, Indra. “Privatisasi Air Kabinet Yudhoyono,” dalam http://wong-mbatu.com/utama/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=9 diakses pada tanggal 11 November 2008 pukul 21.35 WIB.
Wiliamson , John. “What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?”, dalam http://216.239.57.104/search?q=cache:NUokfgXfzzgJ:www.worldbank.org/research/journals/wbro/obsaug00/pdf/(6)Williamson.pdf+World+Bank+from+Washington+consensus+to+post+Washington&hl=en&ie=UTF-8 , diakses 21 September 2008, pukul 18.00 WIB.
Stiglitz, Joseph. Globalisation and It’s Discontents, (New York: W.W. Norton & Company, Inc.), 2002.
Ditulis oleh Pandu Utama Manggala
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI
Ketua Umum BEM FISIP UI
<
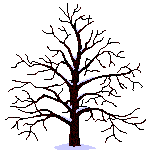


|